Mengenang Si 'Anak Desa' Sembari Membayangkan Politik Bertabur Bintang
Konten dari Pengguna
27 Januari 2018 17:34 WIB
Tulisan dari Muhammad Darisman tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
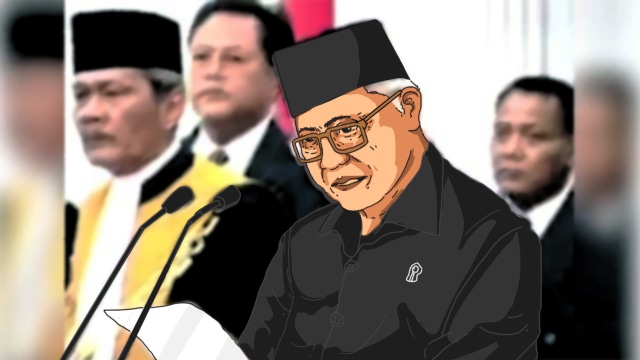
ADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Tepat hari ini, satu dekade sudah presiden ke-2 Republik Indonesia disemayamkan. Jenderal Besar TNI (Purn.) H.M. Soeharto mengembuskan napas terakhirnya karena mengalami kegagalan fungsi beberapa organ tubuhnya. Ia meninggal di Jakarta pada 27 Januari 2008 dalam usia 86 menjelang 87 tahun.
ADVERTISEMENT
Saya mencoba mengenang dan membayangkan seperti apa sosok beliau, lebih tepatnya, membayangkan seperti apa Orba yang begitu panjang itu di bawah pimpinannya. Dari semua Presiden Indonesia, dialah yang paling lama memimpin, yakni sejak tahun 1967-1998 atau selama 32 tahun.
Tentu saya hanya bisa membayangkan sembari meraba-raba sejarah tentang dirinya, sebab saya tidak merasakan langsung Orde Baru itu seperti apa. Bahkan Kerusuhan Mei 1998 yang melengserkan kekuasaannya pun-- yang pada waktu itu sudah bisa saya lihat di televisi-- tidak saya mengerti sama sekali.
Beberapa tahun setelah itu, ketika telah tiga kali presiden berganti, baru saya sering mendengar celoteh kerabat saya tentang Pak Harto (begitu mereka menyebutnya). Apalagi jika BBM atau sembako sudah naik, pasti mereka kan berkata lebih enak zaman Pak Harto, semua kebutuhan murah.
ADVERTISEMENT
Itu perkenalan pertama dengan nama beliau. Sementara potret wajahnya, saya kenali kemudian berkat truk lintas Sumatra yang lalu-lalang di rumah saya. Gambaran yang paling saya ingat adalah foto dia tersenyum sembari melambaikan tangan. Menariknya, pasti selalu dihiasi tulisan Piye kabare? enak’an jamanku to le? atau ada lagi tulisan Iseh penak zamanku.

Sosok yang dikenal dengan sebutan "The Smiling General" (jenderal yang tersenyum), yang saya tahu, begitu melekat di hati rakyatnya. Mulai dari bapak pembangunan, Penolong kaum tertindas, presiden rakyat kecil, dan berbagai sebutan lainnya dilekatkan pada sosok itu. Pokoknya masyarakat kelas bawah dan generasi 80-an begitu mengidolakannya, menjadi seperti Presiden Soeharto adalah sebuah cita-cita keren menurut mereka.
Kemudian, melalui beberapa biografi tentang Soeharto, ia ingin menegaskan diri sebagai sosok sederhana yang berasal dari desa-- bukan sosok Bapak Revolusi seperti Bung Karno, Bung Besar yang berapi-api. Hal ini terlihat salah satunya dalam biografi yang ditulis Otto Gustav Roeder berjudul The Smilling of General: President Soeharto of Indonesia (1969). Buku tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto (1990).
ADVERTISEMENT
Buku tersebut menggambarkan bahwa Soeharto adalah sosok anak desa yang merasakan kegetiran hidup sejak kecil. Banyak penderitaan yang telah ia lalui menjadikannya sosok yang kuat. Sehingga akhirnya ia bisa memimpin Indonesia selama tiga dekade lebih.
Sampai di sini, satu hal yang saya simpulkan bahwa Soeharto adalah presiden yang merakyat. Namun, memasuki masa-masa kuliah, muncul lagi potongan demi potongan sejarah Orde Baru ke dalam pikiran saya melalui karya-karya sastra. Ini pertama saya dapatkan setelah membaca novel Entrok karya Okky Madasari. Novel tersebut kebetulan mengusung latar dari Orde Lama hingga Orde Baru.
Ada dua simbol yang saya ingat betul dalam Entrok, yaitu pemerintah dan militer. dua hal tersebut adalah yang paling berkuasa dan ditakuti oleh masyarakat. Selain itu diceritakan juga bahwa militer bertindak semena-mena, memungut pajak sesukanya, bahkan dengan mudahnya menghilangkan orang.
ADVERTISEMENT
Nyatanya, Entrok bukan satu-satunya karya yang menggambarkan rezim Orde Baru itu kejam. Ada puluhan karya sastra serupa, sebut saja Ahmad Tohari, Rendra, Nano Riantiarno, Seno Gumira Ajidarma, dan masih banyak lainnya. Kata-kata SGA yang paling saya ingat adalah “Ketika jurnalistik dibungkam maka sastra bicara.”
Ya, pada waktu itu Orde Baru merepresi kebebasan individu. Mereka yang vokal dan dianggap mengganggu stabilitas akan dicekal. Lekra, sastrawan, dan pers, adalah beberapa yang pernah dicekal. Tak hanya dicekal, ancaman penjara bahkan sampai dihilangkan pun akan menghantui mereka yang bersuara. Mereka yang merasakan dinginnya tahanan di antaranya Sitor Situmorang, W.S. Rendra, A.M Fatwa, bahkan Wiji Thukul yang hilang begitu saja.
Ada satu tokoh lagi yang sampai akhir hayatnya benar-benar memusuhi Soeharto. Ia tak lain adalah Pramudya Ananta Toer, seorang sastrawan yang merasakan penjara sejak penjajahan, Orde Lama, hingga Orde Baru.
ADVERTISEMENT
Keduanya datang dari generasi yang sama serta memiliki latar belakang militer, walaupun akhirnya Pram lebih memilih jadi penulis. Ketika Soeharto jadi presiden, Pram lah yang secara tajam mengkritiknya. Akhirnya Pram mendekam selama 10 tahun di Pulau Buru dan harus menjalani kerja paksa.

Demikianlah kurang lebih gambaran mengenai si ‘Anak Desa’ yang saya dapatkan secara tidak langsung itu. Saya coba membayangkan seperti apa ketakutan masa lalu masyarakat terhadap militer. Atau mengira-ngira adakah para bintang atau jenderal kala itu yang dengan gagah perkasa memimpin pembantaian. Tetapi tetap saja saya gagal membayangkan.
Malah yang muncul di pikiran saya hanyalah soal hari ini, berapa banyak bintang yang mulai terjun ke dunia politik. Terlebih, beberapa hari belakangan yang sedang hangat adalah soal jenderal yang rencananya akan ditunjuk menjadi PJ Gubernur. Rencana ini menimbulkan pro kontra berkepanjangan di kubu politik, di pemerintahan. Sementara saya hanya gagal memikirkan keduanya dan malah memunculkan pertanyaan baru, apa mungkin negara ini mengalami de javu? ah tentu saja tidak mungkin.
ADVERTISEMENT
Pada akhirnya, karena mengenang Presiden Soeharto, pikiran saya kembali digiring pada sebuah pertanyaan “Enak zamanku toh le?’’
Apa memang benar sekarang tidak lebih baik dari dulu? Jika memang, ya jadi orang yang merugilah kita semua.
(Mengenang 10 tahun kepergian Soeharto)

