Pilihan Politik atau Politik Pilihan
Konten dari Pengguna
27 Februari 2024 11:09 WIB
·
waktu baca 5 menitTulisan dari Julpadli tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
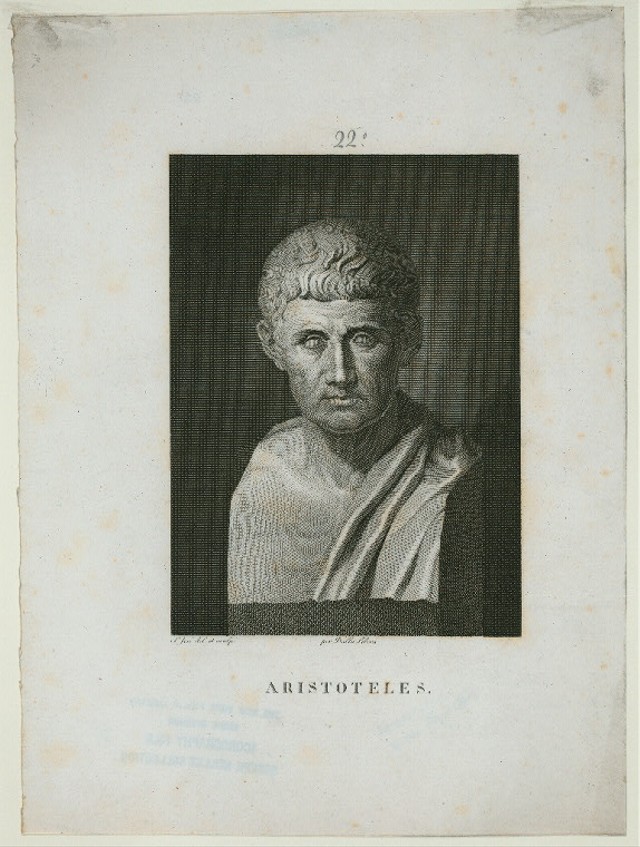
ADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Dalam perjalanan sejarah panjang pemikiran politik, dua nama besar, Giorgio Agamben dan Aristoteles, muncul sebagai panduan utama bagi para pemikir yang ingin memahami dinamika kompleks antara manusia dan pilihan politik. Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi hubungan antara manusia dan pilihan politik dalam kerangka pemikiran Agamben, dengan mengintegrasikan landasan pemikiran Aristoteles dari karyanya "Politika".
ADVERTISEMENT
Sebelum kita menyoroti kontribusi Agamben dan Aristoteles, perlu dipahami bahwa setiap pandangan tentang politik selalu tertanam dalam kerangka pemikiran filosofis yang lebih besar. Aristoteles, salah satu filsuf terbesar dalam sejarah, memberikan landasan klasik untuk memahami struktur politik dan tujuan hidup manusia. Pemahaman konsep politik dan masyarakat dalam Aristoteles membuka pintu bagi analisis yang mendalam terhadap pemikiran Agamben.
Dalam karya monumentalnya, "Politika", Aristoteles menyelidiki struktur masyarakat, bentuk pemerintahan, dan tujuan hidup manusia. Bagi Aristoteles, politik tidak hanya tentang pemerintahan, tetapi juga tentang pencapaian tujuan hidup yang baik. Konsep "eudaimonia" atau kebahagiaan yang berkelanjutan menjadi fokusnya, yang memandu individu dan masyarakat ke arah tujuan hidup yang bermakna.
Sementara Aristoteles menyediakan landasan klasik, Agamben membawa kita ke dalam abad ke-20 dengan konsep Homo Sacer. Dalam pemikirannya, Homo Sacer menjadi manusia yang terkecuali, diabaikan oleh hukum, dan terjerat dalam situasi politik yang membatasi kebebasannya. Pada titik ini, pertautan antara pemikiran Aristoteles dan Agamben muncul — bagaimana manusia, yang Aristoteles gambarkan sebagai pencari kebahagiaan, bisa berakhir di wilayah Homo Sacer, dikecualikan dan dihancurkan oleh kekuasaan politik?
ADVERTISEMENT
Dengan menggabungkan pemikiran Aristoteles dan Agamben, tulisan ini bertujuan untuk menelisik sedikit terkait hubungan yang kompleks antara manusia dan pilihan politik dalam kerangka pemikiran Agamben. Kita akan menyelidiki bagaimana pemahaman Aristoteles tentang tujuan hidup manusia mempertajam analisis kita terhadap konsep Homo Sacer, membawa kita pada pertanyaan kritis mengenai kebebasan, hak asasi manusia, dan dinamika politik kontemporer.
Agamben memperkenalkan konsep Homo Sacer sebagai subjek yang dikecualikan dari perlindungan hukum, menjadi "manusia suci" (dalam buku terjemahan berbahasa Indonesia Homo Sacer juga diartikan manusia suci namun saya lebih memilih mengartikannya sebagai manusia marjinal), yang dapat dihancurkan tanpa melanggar hukum.
Pertanyaan mendasar pun muncul: bagaimana manusia, dengan aspirasi Aristoteles untuk mencapai kebahagiaan dan kehidupan bermakna, bisa berakhir dalam keadaan Homo Sacer? Bagaimana keadaan pengecualian dapat mempengaruhi pilihan politik manusia?
ADVERTISEMENT
Dalam kerangka ini, kita akan menyelidiki bagaimana keadaan pengecualian — situasi darurat atau kebijakan pengecualian tertentu — dapat membentuk pilihan politik manusia. Apakah pilihan tersebut muncul sebagai respons terhadap ancaman terhadap kebahagiaan dan kebebasan individu, ataukah justru sebagai hasil dari manipulasi kekuasaan yang memaksa manusia masuk ke dalam wilayah Homo Sacer?
Di Indonesia, situasi darurat atau keadaan pengecualian tertentu memang tidak secara tegas muncul di permukaan. Namun, indikasi derivatif yang memungkinkan terjadinya pengecualian dapat dianalisa. Kita dapat mengambil contoh dari bagaimana UU ITE menjadi pembahasan pro-kontra.
Pemerintah menilai UU ITE sebagai sarana perlindungan terhadap kebebasan ekspresi dan berpendapat. Sedangkan disisi lain, tidak sedikit kalangan yang berpendapat UU ITE dapat mengancam kebebasan ekspresi dan berpendapat setidaknya dalam beberapa pasal yang dinilai memiliki ketidakjelasan dan dapat ditafsirkan secara subjektif.
ADVERTISEMENT
Pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE setidaknya merupakan pasal yang beberapa kali digunakan dalam memperkarakan ekspresi dan pendapat masyarakat di ruang digital. Pasal 27 ayat 3 tersebut berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. Sedangkan pasal 28 ayat 2 memuat persoalan penyebaran informasi yang menimbulkan permusuhan, kebencian dan mengandung unsur SARA.
Meskipun pada tanggal 2 Januari 2024, Presiden Jokowi telah menandatangani revisi kedua atas UU ITE namun setidaknya terdapat 18 perubahan dalam UU ITE tersebut, sebagaimana dikutip melalui Tempo.co, berpotensi dapat disalahgunakan. Sejak disahkan pada 2008 dan direvisi pertama kali pada 2016, UU ITE telah mengkriminalisasikan pembela Hak Asasi Manusia (HAM), jurnalis, perempuan korban kekerasan seksual dan warga yang melontarkan kritik sahnya (SAFEnet, 4 Januari 2024).
Laporan Pemantauan Hak-hak Digital Tw III 2023 yang dirilis SAFEnet menyebutkan beberapa hal penting seperti adanya indikasi gangguan akses internet berkolerasi dengan situasi politik, hukum dan keamanan terkait Papua. Pada periode tersebut terdapat pemblokiran situs layanan digital seperti Google Docs, Sheets dan Slide pada tanggal 21 September 2023. Pemerintah hanya berdalih dengan faktor ketidaksengajaan.
ADVERTISEMENT
Pemerintah sebagai pemegang otoritas, memiliki kontrol penuh atas hak akses informasi dan ruang digital. Dengan dalih ketidaksengajaan dan penggunaan pasal multitafsir, pemerintah dapat menciptakan situasi di mana individu ataupun kelompok masyarakat dianggap sebagai Homo Sacer yang terbungkam oleh sikap kritisnya.
Di sisi lain, hadirnya para pendengung atau buzzer di ruang digital menciptakan polarisasi propaganda yang memungkinkan terjadinya misinformasi. Lebih lanjut, dalam buku Manufacturing Consent: The Political Economy of The Mass Media karya Edward S. Herman dan Noam Chomsky diterangkan bahwa salah satu model propaganda adalah Manufacturing Consent yang dapat diartikan sebagai upaya terstruktur dan sistematis melalui berbagai media baik berupa iklan, hiburan dan berita untuk menanamkan nilai-nilai, keyakinan dan perilaku tertentu demi kepentingan tertentu yang sering didominasi oleh kaum elit dan penguasa.
ADVERTISEMENT
Masyarakat yang telah diubah menjadi kerumunan bilangan-bilangan (algoritma) tunduk pada stimulus-responsif melalui kemudahan akses digital dan media informasi untuk kemudian dikelompokkan berdasarkan kepentingan popular.
Dengan pengaruh media sosial dan kontrol informasi, pemerintah dapat membentuk persepsi masyarakat berdasarkan klasifikasi tertentu seperti kecenderungan politik, tingkat pendidikan, jenis kelamin, orientasi seksual dan lain sebagainya.
Pada kondisi ini pula, secara tidak langsung masyarakat diarahkan untuk tidak memiliki pilihan politik bebas dan kritis. Sementara pemerintah bisa saja terjebak pada konsep totalitarianisme meskipun semu dengan melahirkan wilayah Homo Sacer bagi rakyatnya sendiri. Yang kritis dibungkam, yang awam tak punya pilihan.

